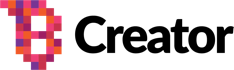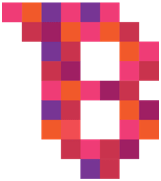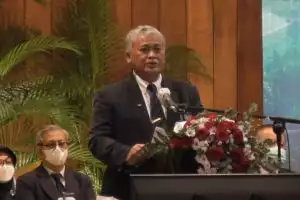Kasus pelecehan seksual sepertinya tidak memiliki titik henti, dan yang kerap menjadi korban adalah kaum perempuan. Komnas Perempuan melaporkan pada tahun 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual pada kaum hawa, lalu di tahun 2015 tercatat ada 6.499 kasus, dan pada tahun 2016 telah terjadi sebanyak 5.785 kasus. Bila di masa lalu perempuan khawatir dan diwanti-wanti agar selalu waspada akan potensi terjadinya kekerasan seksual saat berada di lokasi sepi dan berjalan seorang diri, kini di tempat-tempat seperti rumah, lingkungan pekerjaan, bahkan institusi pendidikan, kasus pelecehan seksual semakin sering terjadi.
Data MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menunjukkan kekerasan seksual di rumah mencapai angka 37 persen, dalam lingkungan profesi informal sebesar 15,3 persen, dan di sekolah sebanyak 11 persen. Fakta ini tentu membuat kita miris karena sepertinya sudah tidak ada lagi tempat yang benar-benar bisa memberi jaminan rasa aman kepada kaum perempuan.
Di samping itu, korban kekerasan seksual sering tidak mendapatkan pendampingan hukum yang berkeadilan. Lihat saja kasus Afni (nama samaran), mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengalami kasus pelecehan seksual oleh rekan satu kampusnya saat menjalani praktik Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku. Kasus itu terjadi pada 30 Juni 2017 dan pada medio Desember 2017, Afni baru memberanikan diri melapor. Dalam ikhwal kronologis kejadian, upaya-upaya pemulihan psikologis dan pendampingan hukum korban seperti yang dilansir dari Majalah Kampus UGM, Balairung Press terdapat sederet lika-liku yang membuat penyintas belum memperoleh keadilan hukum. Belakangan malah kasus itu berujung damai. Kuasa hukum Afni, Sukiratnasari (dilansir dari laman tirto.id) menyatakan proses hukum yang kian rumit dan posisi kliennya yang semakin terjepit menjadikan solusi ini sebagai yang terbaik.
Budaya patriarki.
Barangkali terjadinya tindakan pelecehan seksual juga sedikit banyak dipengaruhi oleh fakta bahwa mayoritas suku di Indonesia mengusung sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Tak pelak, posisi kaum perempuan sering dianggap tidak sepenting kaum laki-laki. Stigma bahwa perempuan hanya berperan melahirkan anak dan sebagai ibu rumah tangga mengurusi persoalan dapur dan beres-beres rumah masih banyak melekat di sebagian besar masyarakat. Akhirnya posisi kaum perempuan menjadi semakin inferior dan kaum laki-laki menjadi semakin superior.
Walaupun gerakan emansipasi wanita sudah digagas Raden Ajeng Kartini dan sekarang kaum perempuan mulai menunjukkan eksistensi kesetaraan mereka dengan kaum laki-laki, masih terdapat begitu banyak diskriminasi gender dalam konteks kehidupan sehari-hari.
Mari kita lihat bentuk diskriminasi dari segi bahasa. Implikasi menganut budaya patriarki terhadap diskriminasi jender melalui bahasa setidak-tidaknya diejawantahkan dalam beberapa hal.
Pertama, kita cenderung menggunakan frasa Bapak/Ibu yang saya hormati dalam berbagai pidato. Ini memang terdengar sepele, tapi meletakkan kata Bapak mendahului kata Ibu yang sudah mendarah daging mencerminkan bahwa dalam bertutur pun kita lebih mengagungkan kaum laki-laki. Bandingkan dengan, misalnya, Bahasa Inggris yang justru memakai ungkapan Ladies and Gentlemen atau ekspresi Ladies first.
Kedua, kalimat Jono menikahi Tuti terdengar lebih lazim ketimbang Tuti menikahi Jono. Dan lagi-lagi jika hendak membandingkan dengan Bahasa Inggris, Jono married Tuti atau Tuti married Jono adalah dua kalimat yang sama berterima karena marry (menikahi) bersifat resiprokal sehingga siapa pun subjek kalimat-laki-laki atau perempuan-menjadi sah-sah saja. Artinya ada konsistensi kesetaraan di sana. Berbeda dengan Bahasa Indonesia, menikahi adalah pekerjaan yang dilakukan laki-laki sebagai subjek dan perempuan menjadi objek. Menempatkan perempuan sebagai subjek pada konteks kalimat seperti ini bisa jadi malah terdengar aneh dan dipertanyakan.
Ketiga, lema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengindikasikan begitu banyak kolokasi kata perempuan atau wanita dengan kata-kata lain yang berkonotasi negatif, semisal perempuan jalang, perempuan sundal, perempuan malam, perempuan nakal, perempuan cerewet, wanita panggilan, wanita tuna susila, wanita kotor dan lain-lain. Sebaliknya untuk kata laki-laki atau pria hasilnya cenderung lebih sedikit meski terdapat ungkapan yang lebih meninggikan marwah perempuan seperti pada frasa Ibu Pertiwi atau Ibu Kota.
Diskriminasi gender lewat bahasa juga kerap tersaji di media, khususnya ketika memberitakan kasus pelecehan seksual. Media sering memakai headline yang cenderung memberi ekspos berlebih pada kaum perempuan sebagai korban. Lihat saja contoh judul berikut, Nyaris Terjatuh Akibat Payudara Diremas, Korban Pelecehan Lapor Polisi (Sindonews). Tipikal headline macam ini kerap ditemukan di banyak media cetak dan portal berita dalam jaringan. Dari judul itu, tak satu kata pun merujuk atau memberi keterangan mengenai pelaku. Semuanya lebih mengumbar deskripsi korban dalam bahasa yang cukup vulgar dan mengandung unsur seksisme.
Artinya, suka atau tidak, media sudah ikut-ikutan melakukan tindakan kekerasan seksual secara simbolik dengan judul-judul berita yang mendiskreditkan korban. Kadang fenomena ini semakin diperparah dengan pengungkapan identitas korban seperti nama asli (bukan inisial), alamat, dan foto korban yang kadang tidak di-blur. Ironisnya, selain mendapatkan porsi informasi yang cenderung sedikit dalam judul berita, identitas pelaku sering kurang tersampaikan dan malah foto-fotonya sering dibuat buram. Padahal yang seharusnya terjadi adalah kebalikannya agar pelaku mendapat rasa malu akibat perbuatannya.
Dunia kerja juga tak luput dari bentuk perilaku diskriminasi pada kaum hawa. Badan Pusat Statistik pada Februari 2018 silam mencatat rata-rata upah atau gaji pekerja perempuan berada pada angka 2,2 juta rupiah per bulan. Sementara untuk laki-laki nilainya lebih tinggi yakni mencapai 2,91 juta. Kesenjangan upah ini terjadi di banyak sektor pekerjaan. Bahkan, meski mengecap pendidikan yang lebih tinggi, upah yang diterima perempuan relatif lebih rendah.
Satu faktor yang ditengarai menjadi pemicu adalah UUD Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 31 ayat 3 undang-undang itu mengisyaratkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dengan demikian, ketika perempuan menjadi pekerja, meski faktanya adalah pencari nafkah utama dalam keluarga, mereka tetap dianggap pekerja lajang sehingga hak seperti tunjangan keluarga tidak diperoleh. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa dunia kerja kita yang semestinya berlandaskan objektifitas serta mengedepankan kinerja dan prestasi ternyata masih dipengaruhi aspek sosio-kultural yang menempatkan perempuan di kasta kedua di bawah laki-laki.
Mengenali bentuk pelecehan seksual.
Bentuk pelecehan seksual beranekaragam jenisnya. Ini harus benar-benar diketahui masyarakat luas, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Pasalnya bisa saja sebuah tindakan dirasa wajar, baik oleh kaum laki-laki atau perempuan, tapi ternyata perbuatan itu sudah masuk kategori pelecehan seksual.
Komnas Perempuan menyatakan pelecehan seksual merujuk pada tindakan yang bernuansa seksual, baik lewat kontak fisik maupun non-fisik dan menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Selama ini, mungkin, masyarakat hanya mengeneralisir ruang lingkup pelecehan seksual pada hal-hal yang bersifat kontak fisik. Padahal, siulan, kedipan mata, bahasa vulgar dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sudah masuk kategori pelecehan terlebih bila perilaku-perilaku ini menyebabakan ketidaknyamanan, rasa tersinggung, merasa martabatnya direndahkan hingga mengakibatkan depresi, ketakutan, serta masalah kesehatan dan keamanan.
Pada kasus Afni, selain pelecehan yang dilakukan HS, sadar atau tidak sadar, bentuk pelecehan lain juga muncul kala seorang pejabat di lingkungan UGM yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan Ibarat kucing kalau diberi gerah (ikan asin dalam Bahasa Jawa), pasti kan setidak-tidaknya akan dicium-cium atau dimakan. Selain sebagai bentuk victim blaming, diksi ini sangat menyedihkan karena disamping menganalogikan korban sebagai, maaf, ikan asin juga terkesan sangat menyudutkan. Seolah-olah korban menyodorkan, lagi-lagi maaf, rangsangan seksual pada pelaku.
Analogi ini sering muncul dan terkesan menyalahkan pihak perempuan agar lebih menjaga tata cara berpakaian. Laki-laki memang lebih visual dalam konteks pandangan seksual dibandingkan perempuan. Perempuan tidak akan terangsang secara seksual ketika melihat pria berbadan atletis sedang bertelanjang dada memamerkan perutnya yang six packs. Tapi laki-laki berbeda. Dengan melihat bagian-bagian tertentu tubuh wanita atau hanya sekedar membayangkan, nafsu seksualnya bisa muncul seketika.
Namun demikian perbedaan ranah biologis dan psikologis ini tidak serta merta membenarkan perbuatan laki-laki melakukan pelecehan seksual mana kala misalnya melihat perempuan yang, baik disengaja atau tidak, menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu sehingga menimbulkan hasrat seksual. Sebabnya manusia dikarunia akal pikiran dan hati nurani yang semestinya bisa mengendalikan diri dari perbuatan tercela. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Hewan hanya mengandalkan insting. Maka tak heran ketika anjing, kucing atau ayam ada yang mengawini ibu, kakak atau anaknya sendiri. Jika laki-laki tidak mampu menggunakan akal sehat untuk mengendalikan diri dari perbuatan kekerasan seksual, maka ia tak ada bedanya dengan hewan-hewan tadi. Akan tetapi ada baiknya juga apabila kaum perempuan lebih tanggap melihat situasi dan kondisi ketika memilih pakaian yang hendak digunakan untuk meminimalisir terjadinya tindakan pelecehan seksual.*
*Penulis berprofesi sebagai guru dan dosen, aktif mengisi kolom opini beberapa surat kabar dan portal media dalam jaringan.