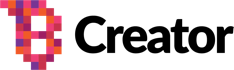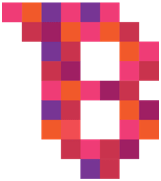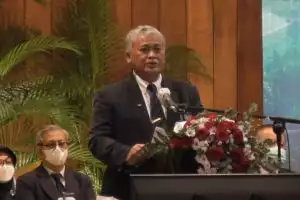Bagi perempuan yang sedang merasa tidak stabil secara emosional, meluapkannya dengan menangis tentu akan melegakan. Namun tidak begitu dengan laki-laki. Berbagai stigma telah terbangun di masyarakat kita bahwa laki-laki yang menangis atau bahkan hanya mengungkapkan perasaannya saja adalah laki-laki yang lemah, selayaknya perempuan, ataupun tidak manly.
Perspektif sempit tersebut hanya sebagian kecil dari gambaran toxic masculinity dalam masyarakat kita. Yuk, simak lebih lanjut tentang toxic masculinity untuk mengetahui apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi perspektif tersebut.
Toxic masculinity.

Istilah toxic masculinity dilaporkan pertama kali digunakan oleh seorang psikolog Shepherd Bliss pada tahun 1990an untuk memisahkan dan membedakan sifat positif dan negatif yang dimiliki laki-laki.
Mengutip dari Urban Dictionary, toxic masculinity didefinisikan sebagai sebuah istilah sosial yang menggambarkan perspektif sempit tentang peran gender laki-laki. Toxic masculinity mendefinisikan seorang laki-laki yang maskulin harus memiliki standar maskulinitas seperti agresif secara seksual, tangguh, hingga tidak menunjukkan emosi secara terbuka.
Beberapa nilai yang terbangun dari perspektif toxic maskulinity di antaranya seperti laki-laki perlu menjadi dominan dan agresif agar mendapat rasa hormat, interaksi perempuan dan laki-laki yang selalu harus kompetitif, laki-laki sejati harus kuat dan tidak menunjukkan emosi secara terbuka kecuali emosi kemarahan, ataupun laki-laki tidak bisa menjadi korban pelecehan.
Toxic masculinity dan kesehatan mental.

Perspektif toxic masculinity yang telah mengakar di masyarakat menyebabkan anak laki-laki juga harus menanggung beban tersebut sejak dini. Akibatnya berdasarkan penelitian yang dikutip psychologytoday.com, semenjak kecil anak laki-laki jauh lebih mungkin didiagnosis mengalami Attention-Deficit Hyperactivity Disorder serta menerima hukuman yang lebih keras di sekolah daripada anak perempuan sebayanya.
Masih menurut sumber yang sama, meskipun perempuan memiliki kemungkinan 40% lebih tinggi daripada pria untuk mengalami depresi, bukan berarti laki-laki terbebas dari belenggu masalah kesehatan mental. Namun sayangnya mayoritas laki-laki tidak menghadapi masalah kesehatan mental tersebut sama seperti yang dilakukan perempuan, yaitu dengan mencari bantuan kesehatan mental profesional.
Laki-laki menjadi kelompok yang memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mencari layanan kesehatan mental dibandingkan dengan perempuan. Salah satu faktor utama yang dituduh bertanggung jawab atas fenomena tersebut tentu saja toxic masculinity. Dalam perspektif toxic masculinity, laki-laki yang menunjukkan emosi mereka secara terbuka dan mencari bantuan mengatasi masalah kesehatan mental mereka akan terstigmatisai menjadi laki-laki yang sensitif ataupun laki-laki yang lemah. Padahal tidak ada yang salah dengan mengungkapkan perasaan. Sebaliknya berbagai penelitian yang ada menunjukkan ketidakleluasaan mengekspresikan emosi memperbesar risiko terjadinya masalah psikologis dan kesehatan fisik pada laki-laki.
Mayoritas laki-laki mengompensasinya dengan kurang tepat.

Hasil dari berbagai tekanan di atas, laki-laki mengompensasi ketidakmampuan mengungkapkan emosi terbuka tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan adiktif dan berbahaya. Dalam jurnal Social Science and Medicine tahun 2007, laki-laki yang berusaha mengikuti stigma maskulin di masyarakat cenderung memiliki kebiasaan berisiko seperti konsumsi alkohol, konsumsi tembakau, hingga kurangnya konsumsi sayuran. Dalam berbagai laporan, angka penyalahgunaan alkohol dan NAPZA didominiasi oleh laki-laki.
Selain itu, angka bunuh diri pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Berdasarkan analisis Fortune pada tahun 2017, laki-laki 3,5 kali lebih mungkin meninggal karena bunuh diri dibandingkan perempuan. Permasalahan tersebut menjadikan laki-laki memiliki harapan hidup 4,9 lebih pendek daripada perempuan.
Pentingnya menormalisasi mengekspresikan emosi.

Adanya usaha campaign salah satunya dari National Institute of Mental Healths yaitu Real Men. Real Depression diperlukan untuk dapat menormalisasi pencarian pelayanan kesehatan mental bagi laki-laki yang sedang membutuhkan bantuan profesional. Meskipun mengikuti konseling profesional sulit dilakukan bagi sebagian laki-laki, namun usaha seperti melakukan konseling secara online atau sedikit bercerita dan berdiskusi dengan sosok laki-laki dan individu di sekitar menjadi langkah kecil baik yang perlu dicoba.
Selain itu kita sebagai individu yang memiliki keluarga, saudara, teman, dan pasangan laki-laki perlu memberikan dukungan secara proaktif dengan mendengarkan tanpa menghakimi serta mendorong mereka mengekspresikan emosinya dengan lebih baik.
Akhirnya perlu dukungan bersama untuk perlahan mengubah stigma maskulinitas yang ada di masyarakat dengan memberi tahu anak-anak bahwa tidak masalah bagi anak laki-laki untuk mengekspresikan dan menunjukkan emosi bahkan menangis.
Permasalahan kesehatan mental tidak berhubungan dengan gender, tidak ada laki-laki atau perempuan yang memilih untuk hidup dengannya. Namun memiliki masalah kesehatan mental tidak lantas membuat kita terlihat lemah, memilikinya tidak membuat laki-laki menjadi kurang manly.
Source
- https://ibpf.org/the-intersection-of-toxic-masculinity-and-mental-illness/
- https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-race-good-health/201902/mental-health-among-boys-and-men-when-is-masculinity-toxic
- https://www.apa.org/monitor/2019/01/ce-corner
- https://www.healthline.com/health-news/toxic-masculinity-mental-health-problems-for-men
- https://www.psycom.net/depression-in-men/depression-in-men-toxic-masculinity/
- https://www.sehatq.com/artikel/toxic-masculinity-dan-bahayanya-bagi-kesehatan-mental-laki-laki
- https://equaliteach.co.uk/toxic-masculinity/