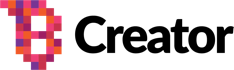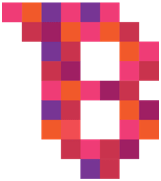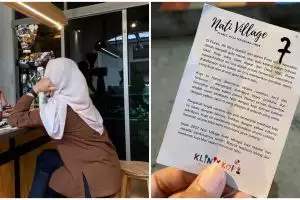Brilio.net - Jogja sudah seperti Gelsenkirchen saja. Gelsenkirchen itu nama kota kategori sedang di Jerman. Setiap tim sepak bola kebanggaan mereka Schalke 04 bermain, seantero kota diselimuti biru. Begitu pula pemandangan di Jogja belakangan ini.
Setiap kali Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram (PSIM) bermain, umbul-umbul dan bendera warna biru putih bertebaran di sudut kota. Banyak pula dipasang di pucuk pohon menjulang tinggi layaknya bendera partai politik pada musim kampanye pemilu.
Sebagai salah satu bond perserikatan tertua, PSIM punya banyak pecinta fanatik. Rata-rata penggemar setia heran, bagaimana mungkin satu dari tujuh klub pendiri PSSI lebih banyak menghabiskan hidup di kasta kedua liga sepak bola nasional akhir-akhir ini. Prestasi PSIM kalah mentereng dibanding pendiri PSSI lain seperti Persija, Persib atau Persebaya.
Maka kemudian asa pendukung melambung musim ini ketika manajemen klub mendatangkan beberapa pemain bintang. Salah satunya bekas striker tim nasional Indonesia naturalisasi dari Cile, Cristian Gonzales. Meskipun sudah gaek, El Loco, sapaan Gonzales diharapkan membawa PSIM ke derajat tertinggi sepak bola nasional.
Belum lama ini saya menyaksikan pertandingan pertama PSIM di Stadion Mandala Krida, Jogja usai dipugar. Lawannya Martapura FC dari Kalimantan. Iklim menikmati pertandingan di stadion baru ini terasa jauh berbeda dibandingkan 20 tahun lalu ketika saya sering menonton pertandingan PSIM kala masih kuliah.
Dahulu kelompok suporter belum terorganisasi rapi seperti sekarang. Paling-paling yang terkenal pentolan suporter, seperti Sandiman misalnya. Penonton hanya akan bersorak kalau tim tuan rumah mendapat peluang gol atau berhasil mencetak gol. Selepasnya lebih banyak celetukan bernada guyonan. Misalnya kalau hakim garis bikin kesalahan, ada yang nyeletuk, Klebete gombal. Lalu ada yang menimpali, Yen klebete seng, yo raiso mabur. Penonton lainnya ketawa, grrrrr.
Sekarang sepanjang pertandingan penonton lebih banyak mendengar nyanyian kelompok suporter. Mereka terus berisik sepanjang 90 menit, seperti tak pernah habis suaranya.
Stadion Mandala Krida, Jogja kini tampak megah dibandingkan dahulu sebelum direnovasi. (Foto Brilio.net/Titis Widyatmoko)
Ada sedikit yang kurang dari konstruksi Stadion Mandala Krida yang baru. Tribun masih beton, belum satu kursi satu penonton (all seater). Tribun all seater ini penting supaya penonton makin nyaman. Keamanan juga terjamin karena kapasitas stadion bisa dikontrol.
Catatan buruk pernah terjadi di Stadion Mandala Krida pada 1995. Seorang penonton Suhermansyah tewas saat pertandingan PSIM lawan Persebaya. Tribun yang kapasitasnya sekitar 15.000 orang ketika itu tidak mampu menampung suporter kedua tim. Tribun terbuka maupun tertutup penuh sesak penonton. Pendukung Persebaya ditempatkan di tribun tertutup. Kemudian terjadi gesekan antarsuporter. Suhermansyah tewas karena terhimpit dan terinjak-injak suporter lain yang kalang kabut menghindari bentrokan.
Tribun all seater sesungguhnya bagian penting dari cara Inggris menghentikan kekerasan di sepak bola. Inggris pernah berpengalaman buruk dengan tragedi Heysel dan Hillsborough. Cara ini namanya bourgeoisification sepak bola. Memborjuiskan sepak bola.
Inggris menyadari selama ini perusuh sepak bola lebih dekat dengan kelas pekerja. Maka sepak bola pun dinaikkan kelasnya supaya bisa dinikmati semua kalangan.
Stadion dibenahi agar wanita dan anak-anak juga nyaman menonton bola. Tribun dengan lapangan dibikin tak berjarak. Tidak ada pagar besi. Tiket dikondisikan berharga mahal. Semuanya dikombinasikan dengan perlindungan keamanan sangat ketat. Aktivitas perusuh perlahan berkurang. Gaungnya dibikin tak bergema.
Mereka menciptakan penonton sepak bola yang mentalitasnya menjadikan ngamuk sebagai pilihan terakhir. Pola pikir penonton baru ini ngalah, ngalih, ngamuk. Kalau ada persoalan mengalah dahulu, menghindari (ngalih) masalah kalau terus ditantang, baru mengamuk kalau tidak ada jalan lain. Pola pikir yang lama, ngamuk selalu nomor satu.
Perjalanan ke arah itu sudah tampak di Mandala Krida. Penjualan tiket semakin rapi lewat online. Kuitansi pembelian bisa ditukar sehari atau pada hari H pertandingan. Tiket bukan lagi berupa karcis tetapi gelang. Cara masuk tinggal memindai barcode. Selain memudahkan penonton, meminimalisir calo, model seperti ini juga mengurangi kebocoran pendapatan tiket.
Sekitar 20 tahun lalu saya menulis sebuah artikel di koran lokal Kedaulatan Rakyat. Inti artikel, untuk menjadi maju PSIM perlu mengelola tim dengan manajemen modern. Begitu juga perlu memikirkan sumber pendapatan lain bagi tim, termasuk mengontrol kebocoran tiket atau menjual merchandise secara resmi.
Harapan saya jauh di masa lalu sudah terwujud sekarang. Ini menunjukkan tanda-tanda maju pengelolaan klub sepak bola di Indonesia.
Sayangnya tak ada gading yang tak retak. Seiring perkembangan dalam menyajikan sepak bola sebagai pertunjukan, problem manajemen dalam mengelola tim masih tampak. Beberapa hari lalu kabar mengejutkan datang dari PSIM. Mereka tiba-tiba menghentikan kontrak 11 pemain ketika musim baru berjalan paruh waktu. Salah satu yang dilepas kontraknya juga pemain naturalisasi bernama Raphael Maitimo. Aneh, baru separuh musim kok 11 pemain sudah dilepas. Kok kayak kambing, diobral setelah lebaran haji, kata seorang kawan.
Harus diakui inilah problem besar banyak tim di Indonesia. Mereka ogah sabar, maunya instan. Padahal kalau menengok Manchester City yang duitnya seperti nggak punya batas, sebenarnya juga punya modal sabar sebelum bisa sampai ke prestasi sekarang. Kalau tim Indonesia, diajak sabar susah banget. Saat nafsu tinggi, akhirnya pemain yang menjadi korban.
Sekilas tampaknya menjadi pemain bola terkesan wah. Tengok saja Neymar yang ketika ditransfer dari Barcelona ke Paris St Germain, digaji Rp 1,5 miliar per hari. Gaya hidup pesepak bola top tampak sangat tinggi.
Padahal, mayoritas pemain sepak bola tidak tergambar seperti yang dtunjukkan para bintang itu. Temuan FIFpro, organisasi yang mewakili para pemain profesional pada 2016 menunjukkan, hanya 2 persen pemain mendapat gaji di atas Rp 10 miliar per tahun. Sebanyak 45 persen pemain di seluruh dunia bergaji di bawah Rp 15 juta per bulan. Sebanyak 21 persen bergaji di bawah Rp 4,5 juta sebulan. Mirisnya 45 persen dari seluruh pemain di dunia pernah mengalami penundaan gaji. FIFpro melakukan survei terhadap 13.876 pemain profesional dari 87 liga di seluruh dunia.
Secara global, sebanyak delapan persen pemain tidak pernah mendapatkan kontrak tertulis. Pemain kebanyakan dikontrak dengan jangka waktu pendek, rata-rata kurun kontrak secara global menunjukkan angka 22,6 bulan. Di Indonesia kebanyakan pemain hanya dikontrak semusim. Itulah yang menjelaskan kenapa di Indonesia jarang ada transfer pemain karena pada akhir musim kebanyakan berstatus free agent.
Bagi para pemain, tekanan tinggi untuk memaksimalkan kemampuan dalam rentang karier pendek memaksa mereka menerima kontrak dengan kondisi buruk. Ketika manajemen klub berpikiran instan, banyak di antara mereka menjadi korban. Penting bagi pemain untuk memiliki konsultan legal maupun humas demi mengamankan karier.
Begitulah realitanya. Dari tepian, dari Jogja, kita bisa melihat kondisi sepak bola nasional. Butuh banyak pembenahan bila muara terakhir yang diharapkan berupa prestasi dunia.