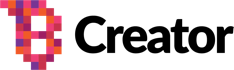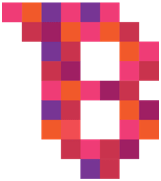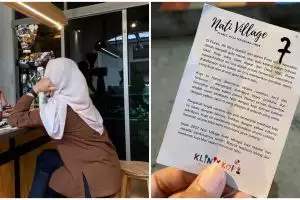Ketika keluar gagasan Malioboro ditutup buat mobil dan motor, para pedagang takut jualannya tak dapat pembeli. Saat trotoar Malioboro sebelah barat jalan bakal ditata, pedagang kembali risau. Bagi mereka yang menggelar lapak menghadap timur, tak masuk akal kalau harus pindah, lalu ungkur-ungkuran dengan PKL menghadap toko.
Malioboro sudah menjadi fokal poin ekonomi Jogja. Dari rel kereta api dekat Stasiun Tugu hingga titik Nol Kilometer, sesak toko, pusat belanja, dan kaki lima. Setiap hari ada 8.000 orang ke Jogja dengan 200 lebih penerbangan. Mayoritas mereka belum merasa ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Kalau dulu Malioboro dijuluki Broadway van Jogja, karena kerlip lampu yang paling terang seantero kota, orang sekarang menyebutnya central business district (CBD)-nya Jogja.
Itulah kenapa setiap kali Malioboro mau diubah, pedagang paling banyak resah. Suaranya paling keras.
Padahal Malioboro tidak melulu uang dan pedagang. Tengok puisi Sitor Situmorang, Malioboro Yogya Pagi Hari. Malioboro sehari-hari juga tentang sopir-sopir taksi di lobi hotel, orang desa ke kota, si mahasiswa, si penyair muda dan si gelandangan. Dahulu Malioboro menghidupi perkembangan seni dan budaya di Jogja. Ada sebutan Universitas Malioboro yang melahirkan seniman dari jalanan. Ada pula istilah presiden Malioboro yang dijabat penyair dari Sumba. Roh seni itu lambat laun kehabisan darah tertikam hedonisme di jantung Malioboro.
Kemudian, segala ribut-ribut tentang rencana penutupan jalan itu berakhir. Kendaraan bermotor dilarang lewat, tidak jadi sepanjang tahun tetapi hanya Selasa Wage. Menurut kalender Jawa, berarti 35 hari sekali. Perdebatan tentang nasib pedagang pun tinggal residu.
Pada hari pertama Selasa Wage tanpa mobil dan motor, seorang penari blasteran Korea-Jawa menjadi viral. Dia memimpin flashmob tarian Jawa Klasik Beksan Wanara. Dunia maya mengelu-elukan. Kota-kota lain ikut mengosongkan jalan, meniru dengan tari kebanggaan daerah mereka.
Belum lama ini kami menemui Mohan Kalandara, penari berusia 12 tahun yang tular itu. Mohan memiliki segala prasyarat untuk viral. Dia bukan jenis viral yang sekejap hilang. Pada usia semuda itu, dia memiliki deep inner strength. Bobot bibit bebetnya kuat.
Mohan Kalandara dan ibunya Jeannie Park di kediamannya yang asri di selatan Jogja. (Foto Brilio.net/Ivanovich Aldino)
Mohan tinggal di rumah dua lantai yang asri di selatan Jogja. Dekat pabrik gula Madukismo. Lantai atas digunakan tempat tinggal, lantai bawah untuk sanggar tari. Ayahnya seniman tari kesohor Lantip Kuswala Daya, ibunya penari cantik berdarah Korea kelahiran Amerika, Jee Hyun-park. Lidah Jawa memelesetkan menjadi Jeannie Park. Anda yang sok Jawa kalah lembut dengan Jawanya Jeannie. Tuturnya sangat halus. Dia ahli menari Jawa klasik. Pengajar tari di Institut Seni Indonesia.
Jeannie mengingatkan saya kepada seorang kerabat, Edwin Wieringa, ahli filologi dari Koln University. Kromo inggilnya elok benar. Baca tulis aksara Jawa jago banget. Kenapa ya, bule-bule ini bisa lebih Jawa dari orang Jawa?
Meski masih belasan tahun, Mohan sudah menguasai banyak jenis tarian. Tayungan, Klana Raja, Klana Alus, Klana Topeng, Wayang Wong, tuturnya. Selama wawancara dia didampingi ibunya. Untuk beberapa pertanyaan yang Mohan masih terbata, ibunya membikin gamblang.
Mohan menari sejak 2016. Dia menyukai tarian yang cepat dan dinamis. Seperti Klana Topeng. Dia kemudian memeragakan tarian ini untuk kami. Ayahnya memegang peranan penting pada keahlian Mohan menari. Yang sering berinteraksi dan mampu menjawab segala pertanyaan, ayahnya sendiri, jelas Jeannie.
Tengok kembali video Mohan menari yang viral itu. Saat dia beraksi, Raja Jogja terpukau. Semua berhenti dari aktivitas. Bus Transjogja yang sejatinya boleh lewat, terpaku menanti. Mohan menjadi penawar bagi ciri utama sebuah kota, serba gegas dan ringkas. Mohan dan kawan-kawan menyumbang sesuatu yang langka di kota: jeda. Bukankah kota juga perlu ruang bernapas?
Pada Selasa Wage tanpa kendaraan bermotor yang kedua, saya bersama keluarga menikmati Malioboro. Jalanan penuh manusia, bagai pasar malam tanpa komidi putar. Kereta angin berbagai rupa di mana-mana. Seorang anak kecil tampak memainkan papan seluncur. Banyak yang duduk di kerb trotoar, tidak khawatir disambar mobil atau motor. Pedestrian terasa menjadi sangat lebar. Sungguh manusiawi.
Suasana trotoar Malioboro yang biasanya dipenuhi PKL tampak lapang. (Foto Brilio.net/Titis Widyatmoko)
Suara obrolan terdengar riuh bagaikan dengungan tawon. Seorang ibu meneriaki anaknya supaya menghindar tumbukan dengan sepeda. Sepasang muda-mudi melepas gandengan tangan. Si cewek menyerahkan telepon pintarnya kepada si cowok, lantas memacak diri di tengah jalan. Tangan si cowok bergerak-gerak mengarahkan si cewek, ibarat koreografer membenarkan langgam penarinya yang kaku. Sadar jadi tontonan, si cewek tersipu mengingatkan cowoknya agar segera mengambil gambar. Saya yakin, sesaat kemudian hormon dopamin cewek itu mengalir seiring pengikutnya menekan tombol love atau like atas gambar yang baru diunggah di akunnya.
Beberapa pengunjung sepertinya baru keluar dari rumah, kamar hotel atau kos-kosan. Harum parfum masih tercium. Bercampur bau keringat anggota klub sepeda yang memenuhi aspal. Di sela itu, asap rokok sungguh menyebalkan. Mohon maaf buat Anda para perokok. Seyogyanya ada tempat khusus merokok, biar puntung dan jerebunya tidak bebas berkeliaran.
Di kaki gerbang kampung pecinan Ketandan, asap bakaran sate mengelun tinggi. Asalnya dari mbok-mbok pedagang sate sunggen dari Madura. Diberi nama sate sunggen, karena perkakasnya selalu disunggi (diusung) di atas kepala. Sate sunggen dijajakan setiap pagi atau sore dengan rute dan jadwal keliling yang terpola. Tanpa asap sate sunggen, saya barangkali ikut percaya hoaks kalau gerbang Ketandan itu berdiri di Shanghai.
Tidak ada mesin meraung. Tidak ada semburan racun dari corong-corong knalpot kendaraan. Suara klakson yang di hari biasa salak-menyalak, dipersilakan menepi. Dari lantai tiga sebuah warung kopi, seorang vokalis membawakan lagu-lagu jazz sembari bercerita baru saja kawan di luar kota mengabari kalau dia selalu kangen Jogja. Kalimatnya tampak datar. Seharusnya dia mengutip saja lisan yang laris di lini masa, bahwa Jogja itu dibangun dari rindu dan kenangan. Eaa. Di bawahnya penonton mendongak, riuh bertempik sorak.
Sebuah hiatus terjadi di kota. Dirasakan warga.
***
Minggu pagi beberapa tahun lalu. Pria tua berkulit hitam pedagang buku itu seakan meneliti tingkah saya. Melihat sorot matanya, saya agak sungkan karena hanya melihat-lihat buku tanpa membeli. Dia menggelar dagangan beralas terpal biru lusuh. Kebanyakan buku-buku terbitan India, buku resep, trik main catur, atau cara belajar main gitar. Buku-bukunya tidak ada menarik perhatian saya.
Bukankah kemarin kamu sudah datang kemari? Dia membuka percakapan, hapal wajah dan tentu kulit sawo matang saya. Sepertinya buku di sini tidak ada yang cocok buatmu? tanya dia. Saya memperkenalkan diri. Kemudian bercerita kalau menginap dekat lapaknya. Sudah lima hari di kota ini, datang dari Indonesia. Dia menyambut uluran tangan saya.
Ketika warga Cape Town, Afrika Selatan menyambut orang Indonesia, dia akan segera menyambungkan obrolan dengan sosok Syekh Yusuf. Ulama asal Makassar itu berstatus pahlawan nasional Afrika Selatan. Syekh Yusuf dan pengikutnya menurunkan generasi melayu Cape Town. Komunitasnya masih bisa ditemui di Bokaap, tak jauh dari pusat kota Cape Town. Di kawasan itu berdiri salah satu masjid tertua di Afrika Selatan. Anak cucu Syekh Yusuf di Afrika Selatan kini sudah sampai keturunan ke-9.
Ke arah timur dari pusat kota menuju Sommerset West, terdapat sebuah perempatan, yang jika berbelok ke kanan memasuki Desa Macassar. Di sana terletak makam Syekh Yusuf. Ziarahlah ke sana, katanya.
Saya mengaku belum sempat. Kemudian bercerita kepadanya kalau dua hari lalu menumpang ferry, menembus laut ujung Afrika, berkunjung ke pulau tempat Nelson Mandela dipenjara. Saya berkata, di sana ada juga pusara orang Indonesia. Nama kuburannya Kramat Moturo. Di situ dimakamkan Sayed Abdurrahman Moturo, salah satu pangeran dari Madura. Moturo adalah imam pertama di Cape Town. Dia dibawa ke Cape Town sebagai tahanan politik VOC dengan kapal laut pada sekitar 1740-an.
Dia asyik mendengarkan cerita saya. Obrolan berlanjut panjang, sampai saya mengatakan akan pulang keesokan harinya. Dia menunjukkan nomor telepon rekannya, seorang sopir taksi. Menawarkan kepada saya apakah besok mau diantar ke bandara. Semula saya ragu. Takut ada sesuatu. Tetapi kemudian mengiyakan. Esok harinya, pada jam sudah kami tentukan, pria pedagang buku dan sopir taksi itu sudah menunggu. Saya diantar ke bandara dengan harga wajar tanpa dikatrol!
Suasana pedestrian St George Mall di Cape Town. (Foto Brilio.net/shutterstock)
Perkenalan dan obrolan itu terjadi di pedestrian selebar 12 meter bernama St George Mall, membujur sepanjang 1,5 kilometer dari gunung ke laut. Dulu St George Mall jalan raya ramai penuh mobil dan motor. Bercampur pejalan kaki. Oleh pemerintah kota, jalanan dibikin zonder mobil dan motor. Murni buat pedestrian. Aspal jalanan dimusnahkan, diganti paving blok. Sekarang, St George Mall ditata indah, untuk pedagang kerajinan, buku, kafe, maupun restoran. Warga kota dan turis menikmati jalan-jalan di sini.
Seperti pengalaman saya. Kehidupan di sana bukan hanya transaksi tapi ada esensi. Tidak cuma jual beli tapi ada relasi. Tidak 35 hari sekali, tetapi setiap hari.
Dunia memberi penghormatan khusus pada Jane Jacobs, seorang wartawan tanpa latar belakang planologi. Jane Jacobs menjadi acuan banyak pakar dan pemerintahan tentang bagaimana menata kota. Buku-bukunya tentang kota, tercetak jutaan kali. Menurut Jacobs, pedestrian itu bentuk seni sebuah kota. Pedestrian adalah panggung sehari-hari untuk sebuah balet yang rumit dimana penari individu atau ansambel, semua memiliki bagian sendiri-sendiri yang secara ajaib memperkuat satu sama lain dan menyusun keseluruhan yang teratur, tulisnya dalam The Sidewalk Ballet diambil dari The Death and Life of Great American Cities. Tak cuma pakar tentang kota, Jane Jacobs pintar dengan kata.
Panggung sehari-hari untuk penari menjadi angan kita terhadap Malioboro. Sayang, membangun kota tidak melulu soal angan. Ada banyak pihak berkepentingan. Angan terhadap Malioboro itu, bisa jadi ditolak pedagang yang memburu uang.
Oleh: Titis Widyatmoko