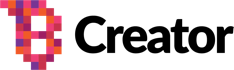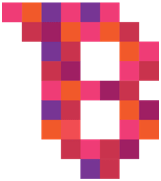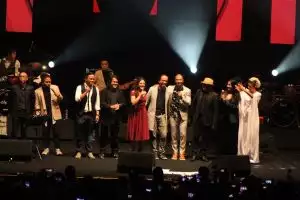Brilio.net - Hidup dari keluarga tak mampu, Sarwidi faham betul bahwa dirinya harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ia pun terpaksa harus putus dari sekolahnya di tingkat yang sangat dini, kelas empat SD.
Sadar pendidikannya tak tinggi, laki-laki asal desa Jarum, Bayat, Klaten, Jawa Tengah ini menyadari bahwa dirinya harus rela bekerja apa saja yang menguras tenaga, demi memenuhi kebutuhannya. Ia mengawalai kerja kerasanya dari menjadi seorang pembantu warung makan di daerah Yogyakarta, penjual buah dingin hingga pekerja bangunan di kawasan ibu kota.
Kerusuhan yang terjadi di tahun 1983 di Jakarta, membuat pria kelahiran Pundung Rejo, 28 April 1972 ini ketakutan dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta. Dengan membawa beberapa uang hasil kerjanya selama di perantauan, Sarwidi akhirnya memutuskan mewarisi pekerjaan orang tuanya sebagai tukang becak.
Bertahun-tahun tak merasakan adanya kemajuan dalam pekerjaan itu, anak kedua dari lima bersaudara ini memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta. Kali ini ia berprofesi sebagai pedagang kaki lima di ibu kota berjualan es, tepatnya di Kedoya, Jakarta Utara.
Tahun 2006 gempa bumi melanda Bantul dan Yogyakarta, kejadian itu nampaknya menjadi sinyal terakhir keberadaannya di Jakarta. Apalagi keadaan sang istri kala itu juga tengah mengandung, sehingga Sarwidi memutuskan untuk pulang kampung dan kembali ke profesi lamanya sebagai penarik becak di Jogja. Ia malang melintang di seputar Yogyakarta mencari penumpang demi menghidupi keluarganya.
Sembari membecak, Sarwidi menjadi buruh pencelup batik pewarna kimia di salah satu perusahaan milik tetangganya. Selama bekerja ia dikirim oleh desa untuk mengikuti pelatihan pewarna alam yang diselenggarakan oleh Balai Besar di Yogyakarta. Entah apa yang melatarbelakanginya, ia begitu senang dengan pelatihan tersebut karena ia merasa benar-benar faham dan ingin menggeluti usaha tersebut.
Sepulang dari pelatihan, keinginan untuk mengembangkan usaha batik pewarna alam begitu besar. Sayangnya kondisi modal untuk memulai usaha yang belum ada, memaksa Sarwidi menjual dua becak yang dimilikinya seharga Rp 950.000 untuk modal usaha.
Sejak saat itu tak kenal lelah. Bertahun-tahun Sarwidi dan istrinya saling bahu membahu mencoba usaha batik pewarna alam dengan ilmu yang didapatnya dari pelatihan. Awalnya ia hanya membuat lima potong batik tulis yang kemudian dengan sepeda ontel dijajakannya dari Klaten ke Yogyakarta.
Tanpa iklan dan promosi, lambat laun Sariwidi mulai dikenal karena batik buatannya berkualitas bagus. Ia pun mendapatkan pesanan dari orang-orang di sekitarnya dan dari mulut ke mulut, Sarwidi mulai dikenal sebagi perajin batik dengan kekhasannya menggunakan pewarna alami.
Meski pembuatannya harus lama dan penuh ketelatenan, Sarwidi dengan sabar menekuni usahanya tersebut. Dia bersaing dengan gempuran batik cap pewarna kimia di pasaran. Namun kedisiplinannya dalam berwirausaha menggunakan pewarna alami, membuat ia banyak dikenal dan diminta untuk menjadi pemateri di berbagai wilayah. Keikhlasannya untuk berbagi pengalaman membuatnya semakin dicintai banyak orang. "Dari dulu saya tidak pernah memasang tarif jika diminta untuk berbagi pengalaman, dibayar seribu pun saya mau," tutur Sarwidi kepada brilio.net, Selasa (5/5).
Kini usaha batik warna alaminya semakin dikenal banyak orang, bahkan oleh wisatawan mancanegara. Wajar jika akhirnya Sarwidi mengekspor batik buatannya ke berbagai negara seperti Kanada, Jepang, dan Australia.