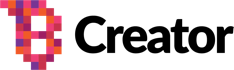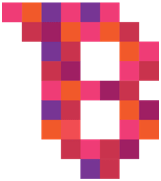Brilio.net - Jam kerja sudah selesai, tapi kamu masih di meja kerja. Tumpukan tugas yang menunggu diselesaikan seakan tak ada habisnya. Ini adalah situasi yang sering dihadapi banyak karyawan di berbagai perusahaan, terutama di Indonesia, di mana lembur menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kantor.
Banyak yang mungkin berpikir lembur hanya terjadi sesekali. Namun, bagi sebagian orang, budaya lembur justru menjadi hal yang dianggap normal. Kamu bahkan mungkin tidak menyadari bahwa lembur ini sudah menjadi rutinitas yang tak terhindarkan. Di balik normalisasi lembur, ada banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari tekanan atasan hingga deadline yang terlalu ketat.
Lembur bukan sekadar tambahan waktu kerja, melainkan juga menggambarkan dinamika yang terjadi di lingkungan kerja. Beberapa karyawan mungkin menganggapnya sebagai bentuk komitmen, sementara yang lain merasa lembur sebagai beban.
Yuk, simak ulasan brilio.net berikut ini seperti dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (23/10) tentang lima budaya lembur yang diam-diam sudah dianggap normal di banyak kantor!
1. Deadline yang terlalu ketat.
foto: freepik.com
Salah satu alasan utama karyawan harus lembur adalah deadline yang ketat. Banyak perusahaan menetapkan tenggat waktu yang nyaris tidak realistis, memaksa karyawan untuk bekerja lebih lama agar pekerjaan selesai tepat waktu.
Beberapa perusahaan mungkin berargumen bahwa deadline ketat adalah bagian dari dinamika bisnis yang cepat berubah. Namun, hal ini seringkali menempatkan karyawan dalam posisi sulit, di mana mereka harus memilih antara menyelesaikan pekerjaan dengan cepat atau mempertaruhkan kualitas hasil kerja. Kondisi seperti ini memicu stres dan kelelahan yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan mental dan fisik.
Dalam jangka panjang, karyawan yang terus-menerus dikejar deadline tanpa ada jeda istirahat berisiko mengalami burnout. Burnout tidak hanya memengaruhi performa kerja tetapi juga menurunkan kualitas hidup karyawan secara keseluruhan. Dengan kata lain, deadline yang ketat sering kali menciptakan siklus lembur yang tak berujung.
2. Budaya 'datang pagi, pulang malam'.
Budaya kerja yang mempromosikan datang pagi dan pulang malam menjadi ciri khas beberapa kantor. Di beberapa perusahaan, karyawan yang datang lebih awal dan pulang lebih larut kerap dianggap sebagai pekerja keras. Hal ini menimbulkan ilusi bahwa bekerja lebih lama berarti lebih produktif.
Beberapa atasan mungkin memberikan penilaian lebih positif kepada karyawan yang sering lembur, meski hal ini bisa jadi tidak berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan. Karyawan yang terjebak dalam pola ini sering kali merasa bersalah jika pulang sesuai waktu. Akibatnya, waktu istirahat dan kehidupan pribadi mereka menjadi terganggu, menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (work-life balance).
Jika terus-menerus dibiarkan, budaya ini bisa merusak kesehatan fisik dan mental karyawan. Sejumlah studi bahkan menyebutkan bahwa terlalu banyak bekerja dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan tidur. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi kembali kebijakan jam kerja dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi kesejahteraan karyawan.
3. Ekspektasi tinggi tanpa batas waktu yang jelas.
foto: freepik.com/azerbaijan_stockers
Dalam beberapa kasus, ekspektasi tinggi dari atasan tidak disertai dengan batasan waktu yang jelas. Karyawan diharapkan untuk selalu siap sedia dan menyelesaikan pekerjaan sesegera mungkin, bahkan jika itu berarti harus lembur hingga larut malam.
Atasan yang tidak menetapkan ekspektasi yang realistis mengenai tenggat waktu sering kali menciptakan tekanan tambahan bagi karyawan. Alih-alih memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan pekerjaan, karyawan justru dipaksa bekerja di bawah tekanan konstan. Akibatnya, banyak karyawan merasa terpaksa untuk lembur demi memenuhi ekspektasi tersebut.
Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana karyawan merasa tidak pernah cukup produktif, meski sudah bekerja lebih keras dan lebih lama. Pada akhirnya, hal ini merusak kesejahteraan psikologis dan fisik mereka, serta menurunkan motivasi kerja.
4. Mengorbankan waktu pribadi untuk pekerjaan.
Lembur sering kali mengorbankan waktu pribadi yang seharusnya bisa digunakan untuk istirahat atau bersantai dengan keluarga dan teman. Banyak karyawan yang menganggap hal ini wajar, terutama jika budaya kantor tersebut memang cenderung mendorong karyawan untuk selalu siap bekerja kapan pun diperlukan.
Jika kamu sering membawa pulang pekerjaan atau terus memeriksa email kantor di luar jam kerja, ini adalah tanda bahwa batasan antara kehidupan profesional dan pribadi telah kabur. Kondisi ini dapat membuatmu merasa tidak pernah benar-benar "lepas" dari pekerjaan, yang menyebabkan perasaan lelah terus-menerus dan kurangnya kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.
Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting. Waktu istirahat yang cukup dan berkualitas akan membantu meningkatkan produktivitas ketika kembali bekerja. Sayangnya, banyak perusahaan belum menyadari pentingnya hal ini dan terus mendorong budaya lembur sebagai hal yang wajar.
5. Tekanan sosial dari rekan kerja.
foto: freepik.com
Tekanan untuk lembur tidak hanya datang dari atasan, tetapi juga dari rekan kerja. Di beberapa kantor, karyawan yang sering pulang tepat waktu mungkin dianggap kurang berdedikasi atau tidak "team player". Tekanan sosial ini sering kali membuat karyawan merasa terpaksa untuk lembur agar tidak dianggap negatif oleh lingkungan kerja mereka.
Ketika budaya lembur sudah mengakar di sebuah perusahaan, sulit bagi karyawan untuk menolak, meskipun mereka tahu dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka.
Tekanan ini bukan hanya soal persepsi karyawan, tetapi juga bagaimana mereka dinilai oleh rekan-rekan dan atasan. Di beberapa kasus, budaya lembur bisa menjadi tolok ukur loyalitas dan komitmen, meskipun hal ini tidak selalu berarti produktivitas yang lebih baik.
Recommended By Editor
- Kerjaan banyak tapi santai, 7 Praktik mindfulness yang kurangi stres sekaligus bikin fokus bekerja
- Dari burnout jadi enjoy kerja, ini 10 cara menciptakan budaya kerja yang sehat di kantor
- 8 Fakta yang nggak akan kamu dengar dari pewawancara saat interview
- 12 Budaya kerja ala startup yang kerap jadi incaran gen Z, suasana kerja seru tapi serius
- Biar nggak gampang capek, ini 10 tips kreatif agar kerjaan cepat kelar