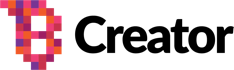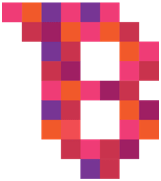Brilio.net - Pandangan berbeda terkait label 'santri' dikemukakan oleh Sohibul Iman di Kertanegara Kamis (9/8). Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan secara sederhana posisi Sandiaga Uno sebagai cawapres mendampingi Prabowo di kontestasi pilpres 2019.
Sohibul mengatakan ingin menggandengkan kepemimpinan nasionalis seperti Prabowo dengan kepemimpinan Islam atau kepemimpinan kaum santri. Namun, Sohibul mengakui dalam kacamata publik Sandi tak masuk dalam kategori santri. Meski tidak memiliki latar belakang pendidikan di pesantren, Sohibul menilai Sandi telah memiliki spiritualisme seperti santri.
"Saya kira beliau memang hidup di alam modern, tetapi beliau melewati proses spiritualisasi dan islamisasi. Sehingga saya bisa katakan saudara Sandiaga Uno sebagai sosok santri di era post-islamisme," ucap Sohibul dilansir brilio.net dari liputan6.com Jumat (10/8).
Publik dibuat penasaran mengenai istilah tersebut, santri di era post-islamisme itu yang bagaimana dan seperti apa? Dr. Amanah Nurish, Peneliti Antropologi Agama yang sedang melanjutkan riset Clifford Geertz di Modjokuto/Pare tentang Islam Jawa, menyampaikan bahwa istilah santri itu lazim dikenal di kalangan tradisionalis. Di kalangan Nahdliyin secara fungsi dan nilai santri tidak berubah karena orang-orang Nahdliyin itu identik dengan pesantren.
foto: Facebook/@Djeng Nurish
Tetapi pasca reformasi dan situasi politik istilah santri menjadi cair di kalangan kelompok Islam modernis dan kelompok Islam transnasional meskipun mereka sebenarnya tidak dekat dengan tradisi pesantren. "Itu hanya dalam rangka mencari perhatian, santri itu istilah NU. Orang modernis tak ada istilah santri, hanya pada tradisionalis." kata Dr. Amanah Nurish saat dihubungi brilio.net, Jumat (10/8).
Dalam kacamata antropologi, menurutnya langkah itu bisa bisa memunculkan terancamnya nilai local wisdom dan prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika. Siasat politik representasi, simbol dan identitas yang diusung sah-sah saja meskipun kemungkinan cara itu tak bekerja optimal, di lain sisi istilah "santri Post-Islamisme" itu bisa jadi sebagai bentuk ketidakpercayaan diri di kubu PKS dan Prabowo. Begitu penjelasan dari Dr. Amanah Nurish.
Sedangkan mengenai Post-Islamis sendiri, Ulil Abshar Abdalla pernah menulis makalah untuk seminar Post-Islamisme dan Demokrasi yang diadakan oleh Forum Lentera Filsafat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia pada 14 November 2011 silam.
Ulil Abshar Abdalla melansir artikel Asef Bayat, seorang sarjana asal Iran yang dikenal karena analisisnya yang tajam tentang gejala post-Islamisme di dunia Islam. Menurut Asef Bayat, revolusi yang bergejolak di dunia Arab sekarang tiada lain adalah revolusi Post-Islamis.
Lanjut Ulil, apa yang disebut sebagai gejala post-Islamisme oleh Asef Bayat mencakup sejumlah fenomena politik di berbagai belahan dunia Islam, mulai dari gerakan reformasi di Iran pada akhir 1990-an, hingga fenomena partai-partai 'tengah' seperti PKS di Indonesia, AKP di Turki, Ennahda di Tunisia, Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko, dan Partai Tengah (Hizb al-Wasat) di Mesir.
Ciri utama gerakan post-Islamisme adalah kecenderungan mereka yang pragmatis, realistis, bersedia untuk kompromi dengan realitas politik yang tak sepenuhnya ideal dan sesuai dengan skema ideologis murni yang mereka yakini dan bayangkan.
"Ciri-ciri umum post-Islamisme di mana-mana memang sama: kompromi dengan kenyataan politik, pragmatisme dalam menjalankan program pemerintah, dan sikap toleran terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Di Indonesia sendiri, gejala-gejala moderasi semacam ini juga kita lihat pada PKS, partai yang oleh Asef Bayat disebut sebagai wakil gejala post-Islamisme di Indonesia. Dalam Munasnya di Bali pada 2008, partai ini menyatakan diri sebagai partai terbuka, inklusif, dan menerima ide pluralisme." tulis Ulil dikutip brilio.net dari islami.co, Jumat (10/8).
Ulil menjelaskan dalam makalahnya, secara umum gejala post-Islamisme ini adalah angin segar bagi dunia Islam, sebab ia menandakan bahwa persepsi tentang pertentangan antara Islam dan demokrasi bisa ditepiskan sama sekali. Demokrasi dan Islam, dalam gejala post-Islamisme ini, bisa bergandengan tangan secara damai, layaknya dua pasangan yang sedang pacaran.
Menurut Ulil, post-Islamisme barulah babak pembuka. Tantangan yang sesungguhnya justru terjadi setelah itu. Pertanyaan yang harus dijawab: jika kalangan post-Islamis sudah menerima demokrasi, dan bersedia ikut dalam gerbong proses elektoral demokrasi dengan segala kerumitannya yang kerap menuntut kompromi tak ideal itu, lalu apa? Whats next?
"Tantangan ke depan ada dua. Yang pertama, apakah komitmen kelompok post-Islamis terhadap demokrasi ini sungguh-sungguh atau dimotivasikan oleh dorongan-dorongan oportunistik sesaat saja, atau oleh kebutuhan politik semasa, political exigencies? Kita tak akan tahu jawabannya selain menunggu sejarah yang akan datang.
Meskipun, tentu, saya tetap optimis, berdasarkan pengalaman-pengalaman serupa di negeri-negeri lain, bahwa pluralisasi kehidupan modern yang membawa kerumitan-kerumitan sosial dalam masyarakat saat ini akan membuat narasi besar Islamis menjadi sulit dilaksanakan, atau bahkan nyaris mustahil, kecuali hanya sebentuk mimpi dan utopia indah yang enak untuk dibayangkan saja.
Kenyataan-kenyataan politik maupun sosial akan memaksa kaum Islamis (atau kaum puritan dalam segala bentuknya di manapun) akan melakukan kompromi, tentu dengan derajat yang berbeda-beda.
Tantangan kedua, dan ini adalah yang jauh lebih krusial: Bagaimana kaum Islamis yang sudah bermetamorfosis menjadi post-Islamis itu akan menerjemahkan agenda-agenda relijius dan ketuhanan mereka dalam ranah kehidupan kongkrit yang penuh dengan kerumitan dan jebakan? Bagaimana mereka akan memperjuangkan agenda itu lewat lembaga parlemen yang diisi oleh aktor-aktor politik dengan aspirasi dan platform yang berbeda-beda?
Pada suatu titik tertentu, kemungkinan terjadinya clash atau tabrakan antara kaum post-Islamis dan kaum non-Islamis memang akan selalu terjadi, terutama dalam memperdebatkan isu-isu tertentu. Semangat konservatisme jelas sangat kuat mewarnai agenda-agenda kaum Islamis maupun post-Islamis di manapun.
Semangat ini akan terlihat saat isu-isu riil diperdebatkan di parlemen. Kasus yang kongkret dalam konteks Indonesia saat ini adalah masalah perlindungan atas hak-hak kaum minoritas, baik minoritas eksternal (seperti Kristen, Hindu dan Buddha) atau minoritas internal (seperti sekte Ahmadiyah).
Tantangan demokrasi ke depan persis terletak di sini: Bagaimana arah demokrasi yang telah hadir sebagai arena terbuka bagi kaum post-Islamis itu di masa-masa mendatang. Corak dan subtansi demokrasi di dunia Islam, dengan masuknya aktor post-Islamis ini, mungkin akan berbeda dengan corak demokrasi yang ada di Barat saat ini.
Tetapi justru di sini soalnya: Seberap besar bedanya? Apakah perbedaan itu, misalnya, akan membawa akibat terabaikannya hak-hak konstitusional yang seharusnya dinikmati oleh semua warga negara atau tidak? Ini sekedar pertanyaan-pertanyaan awal.
Fenomena yang akan kita lihat di masa mendatang tampaknya, mungkin, akan ditandai dengan beragamnya corak demokrasi demokrasi sebagai bentuk jamak, democracies, bukan lagi mufrad sebagaimana kita pahami selama ini, democracy." tulis Ulil Abshar Abdalla dalam makalah tersebut.