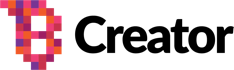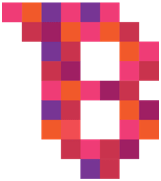Halo kawan Brilio.net, kali ini kami berkesempatan berkunjung ke sanggar sang maestro tari, Didi Nini Thowok. banyak hal tentang dirinya yang ia ceritakan di isi, Yuk kita simak videonya.
Sebenernya stereotip yang timbul di masyarakat itu keliru kalau tari hanya untuk perempuan. Karena tari itu olah rasa, dan kalo kita melihat penari-penari keraton misalnya, itu yang menarikan karakter laki-laki juga laki-laki.
Begitu statement yang diucapkan oleh Didi Nini Thowok atau yang akrab disebut Mas Didi. Nama Didik Nini Thowok tak lagi asing di dunia seni pertunjukan. Ia lahir di lereng Gunung Sumbing, Temanggung tahun 1954. Mulai menari sejak usia 12 tahun yang ia pelajari saat di gereja. Memiliki darah Tionghoa dan bernama lahir Kwee Tjoen An. Pada tahun 1965 namanya diganti ketika heboh tragedi G30SPKI. Menjadi Didik Hadi Prayitno yang hingga kini dijadikan nama resmi. Nama Didik Nini Thowok pun punya cerita di baliknya.
Jadi pada tahun 74, saya kuliah ke Jogja, dari Temanggung saya hijrah ke Jogja. Di Jogja saya ketemu dengan senior saya yang juga dosen dan senior. Beliau namanya Bekti Budi Hastuti dipanggil mba Tuti, yang di kemudian hari, namanya jadi Tuti Nini Thowok ya beliau cerita Didi.
Tari Nini Thowok mulanya karya senior Didik di kampus. Namun saat itu, ia diberi kepercayaan untuk membawakan tarian. Tak disangka, respons baik datang dari banyak pihak. Tari Nini Thowok pun bertengger di mana-mana hingga layar TV. Dari situlah ia dikenal dan orang-orang memanggilnya Didik Nini Thowok. Menyinggung stereotip masyarakat, ia berprinsip kuat. Tetap menjalani pertunjukan lintas gender yang jadi ciri khasnya.
Saya bicara frame seni pertunjukan bahwa banyak sekali stereotip di masyarakat yang nggak pas, keliru sebenarnya. Karena nggak tahu ya nggak disalahkan, pemahamannya masih terbatas" papar Didi.
Ia pun berbagi cerita tentang bagaimana keluar dari berbagai stereotip. Seperti melakukan penelitian hingga mempelajari sejarah.
Kalo saya menari perempuan tidak bisa lebih dari perempuan itu menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya. Kalau saya menunjukkan kualitas, tidak cuma kita yang melihat, dunia luar juga melihat" jelas Didi.
Dalam perjalanannya, menjadi seniman tentu punya banyak tantangan. Meliputi penjiwaan karakter hingga menemukan inspirasi. Membaca buku, menonton pertunjukan di berbagai tempat jadi gudang inspirasi. Saat menjadi karakter perempuan, ia berlatih dengan cara mengamati. Namun ada satu karakter yang paling berat baginya.
Karakter gagah. Bima kan nggak bisa. Bukan nggak bisa, bisa cuman rasanya gak nyampe. Karena saya kalo menari putra gagah kan feminim. Masa Bima rada feminim ya nggak mungkin" ungkap Didi.
Bagi seniman, ritual sebelum pertunjukan bukanlah hal tabu. Termasuk bagi Didi, ia selalu lakukan ritual mandi kembang. Namun tak semua seniman lakukan ritual. Ketika ditanya tentang ritual dan kepercayaan, ia menjawab santai.
Kadang-kadang sering orang mencampur adukkan seni budaya dengan kepercayaan agama, kan jadi nggak nyambung menurut saya kalo dibenturkan nggak akan ketemu pasti terbentur-bentur" tambah Didi.
Ia pun tak menampik banyak seniman yang keblinger. Menjajal cara instan yang ternyata salah dan keluar jalur. Menurutnya ritual harusnya dijadikan sebagai perantara saja. Masalah kepercayaan, hal itu adalah urusan personal.
Ada juga yang begitu minta penglaris supaya bisa jadi kondang, tapi mintanya bukan pada Tuhan. Jalan pintas, pasang susuk, penari ada yang gitu biar pantatnya seksi, dia pasang susuk di pantat. Itu kan sudah pakai alat-alat bantu yang kalo menurut saya pribadi nggak pas, wong minta sama Tuhan dikasih kok malah lebih aman to, nggak pake nagih-nagih atau pantangan-pantangan" tutup Didi.
Recommended By Editor
- Cerita Eross Candra mau isi 1 lagu milik ROKET band baru Jogja
- Seniman asal Indonesia tampilkan karyanya di Amsterdam Light Festival
- Momen Butet Kertaradjasa mengenang Djaduk Ferianto, haru
- Arief Hanungtyas, bangkitkan kenangan lewat lukisan
- Mengenal sosok Anton, fotografer 'Anton Photo' legendaris Jogja